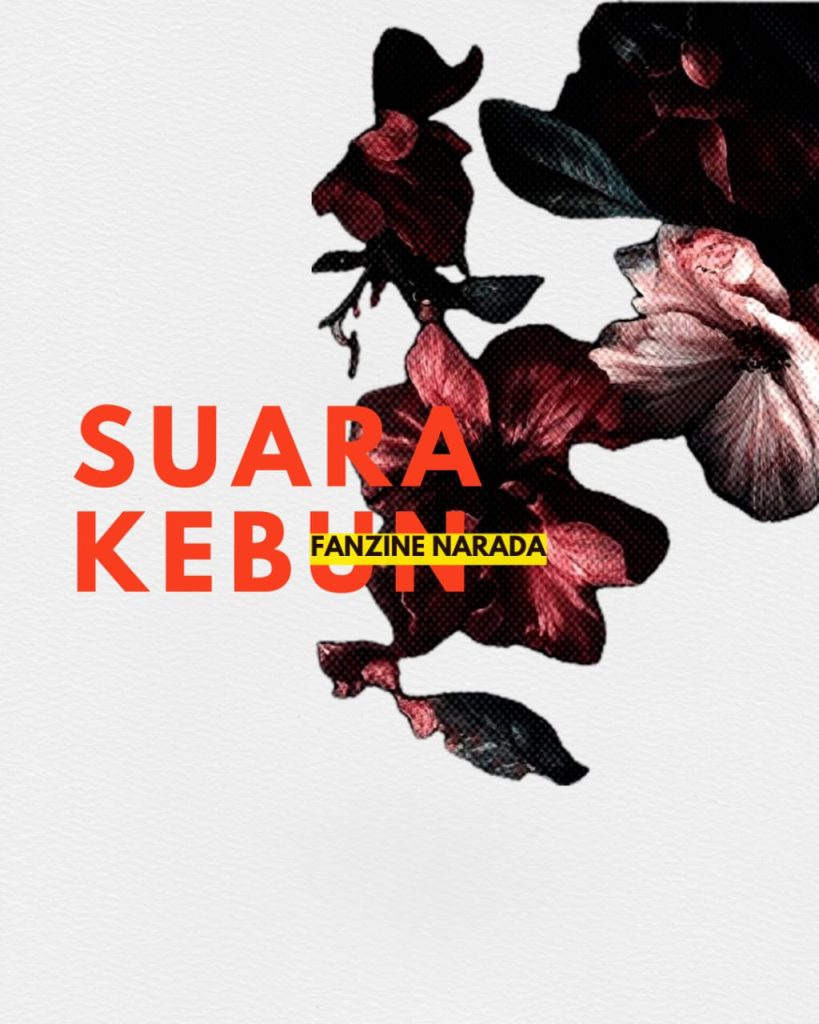Tanah adalah ibu. Pernyataan ini bukan sekadar metafora puitik, melainkan penegasan akan relasi paling purba dan paling sakral antara bumi dan manusia. Tanah adalah tubuh kehidupan itu sendiri—menyerap air mata petani, menumbuhkan benih harapan, dan menyimpan nyawa dalam diam. Tapi dunia modern telah melupakan itu. Tanah tidak lagi dihormati sebagai ibu melainkan dijadikan komoditas, diukur dalam hektar, dijual dalam meter persegi, dan dibajak demi kepentingan kapitalisasi.
Di Bogor, tempat kami tinggal dan menanam, tanah perlahan kehilangan rahimnya. Lahan-lahan subur di kaki Gunung Gede-Pangrango dan Salak terus dikapling menjadi perumahan klaster dan kawasan wisata. Bahkan di tengah kota, ruang hijau hanya menjadi tempelan dalam dokumen tata ruang–bukan kebutuhan ekologis yang dijaga sungguh-sungguh. Bogor yang dulu dikenal sebagai Buitenzorg—tempat peristirahatan kolonial—kini justru jauh dari sifat istirahat. Beton memburu semua yang lembut dan tanah dipaksa bungkam di bawah rataan aspal.
Namun dari luka itu, kami memupuk harapan kecil: Kebun Narada. Sebuah ladang di sudut kota, yang bukan sekadar ruang tanam, tapi ruang bernapas. Ruang belajar, ruang untuk hidup. Narada kami bangun dari tanah bekas—dari lahan yang semula dianggap tak berguna. Kami rawat kembali dengan kesabaran dan cinta. Kami tidak mengejar panen kami mengejar konektivitas dengan tanah, dengan benih, dengan air hujan, dengan cacing-cacing kecil yang menari di bawah humus. Ini bukan sekadar kegiatan berkebun, tapi pernyataan politis, bahwa dalam dunia yang semakin keras, perawatan adalah bentuk lain dari revolusi.
Tidak Ada Masyarakat yang Bisa Bebas tanpa Kebebasan Perempuan
Sistem dunia hari ini menempatkan kerja-kerja itu sebagai yang “tak bernilai”, Kita hidup dalam tatanan ekonomi yang hanya mengakui produksi sebagai ukuran nilai. Sementara perawatan—yang dilakukan oleh petani kecil, ibu-ibu di ladang, dan perempuan-perempuan yang menjaga benih kehidupan—dianggap pinggiran, bahkan beban.
Di sinilah letak kemirisan kita. Bahwa di balik kerusakan ekologi, bukan hanya ada kerakusan kapitalisme dan negara tapi juga cara pandang yang maskulin terhadap dunia. Tanah bukan lagi ibu, tapi obyek. Perempuan bukan lagi penjaga kehidupan, tapi buruh murah. Alam bukan lagi sahabat, tapi sumber daya dan kerja-kerja perawatan—baik terhadap tanah, tubuh, maupun kehidupan—dipinggirkan dari pusat pengambilan keputusan.
Namun dari celah-celah kehancuran itu, tumbuh benih perlawanan. Di Rojava, sebuah wilayah di utara Suriah yang tengah berjuang membangun sistem demokrasi langsung di tengah reruntuhan perang, muncul gerakan yang mendekap kembali tanah, perempuan, dan kehidupan dalam satu napas perjuangan. Di sana, Abdullah Öcalan, pemimpin gerakan Kurdi, mengajukan kritik tajam terhadap kapitalisme, negara, dan patriarki.
Dalam tulisan-tulisannya di penjara dalam kondisi terisolasi total, Öcalan menyebut bahwa “Pembebasan perempuan adalah syarat mutlak pembebasan masyarakat dan alam.” Kesimpulan ini Ia nyatakan, karena Ia melihat bahwa dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam saling berkelindan dan menjadi dasar sistem penindasan sampai sekarang.
Sebagai tanggapan atas itu, perempuan-perempuan di Rojava membentuk apa yang mereka sebut jineologi, ilmu yang lahir dari kata jin (perempuan dalam bahasa Kurdi), yang juga berakar dari kata jin (kehidupan). Jineologi bukan sekadar studi akademik, tetapi gerakan hidup. Ia berusaha membangun kembali relasi yang setara antara manusia, alam, dan komunitas. Dalam praktiknya ini terwujud dalam pertanian kolektif, desentralisasi kekuasaan, dan kesetaraan gender yang konkret. Seperti dicatat dalam laporan Make Rojava Green Again (2018), revolusi ekologis di sana bukan dimulai dari teknologi paling mutakhir. Tetapi dari penanaman, perawatan tanah, dan penyusunan ulang nilai-nilai sosial.
Kita mungkin jauh dari Rojava secara geografis, tetapi secara fenomena ekologi dan politik kita menghadapi luka yang sama. Di Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kami menyaksikan bagaimana tanah-tanah subur dipaksa beralih fungsi demi pembangunan properti. Di bawah bayang-bayang korporasi besar seperti PT. Kahuripan Raya warga Iwul berhadapan dengan proses intimidatif yang berusaha mencabut mereka dari tanah yang mereka rawat turun-temurun.
Tanah yang semula menjadi ruang pangan, spiritualitas, dan gaya hidup keberlanjutan dijadikan objek proyek kota mandiri. Menurut laporan Mongabay (2025), warga yang mempertahankan lahannya dihadapkan pada gugatan hukum dan tekanan aparat, bukan dialog atau pemulihan hak. Perempuan-perempuan Iwul memainkan peran sentral dalam perlawanan ini. Mereka bukan sekadar penjaga dapur tetapi penjaga tanah, penjaga benih, penjaga kehidupan dalam setiap aksi, setiap barisan tanam kembali, mereka menegaskan bahwa merawat tanah adalah hak yang tidak bisa dibeli.
Perempuan-perempuan Iwul dan Rojava tidak saling mengenal. Tapi mereka hidup dalam garis yang sama: Garis luka. Garis tanah. Garis kehidupan. Mereka menunjukkan bahwa perawatan bukan hanya kerja rumah tangga tapi kerja sejarah. Mereka menolak untuk dikalahkan oleh mesin-mesin negara dan kapital dan memilih untuk terus menanam—walau tahu musim bisa tak bersahabat dan hasil bisa tak menentu.
Di Jurang Kehancuran, Selalu Ada yang Tumbuh dan Dirawat
Dalam lanskap dan kesadaran itu juga Kebun Narada berdiri. Tidak hanya sebagai ruang tanam. Tapi sebagai benih solidaritas yang tumbuh dari luka yang sama. Kami merasakan tanah yang ditarik paksa dari akar masyarakat, merasakan dentum alat berat yang membelah suara jangkrik, dan merasakan betapa mengolah tanah hari ini adalah keputusan politis.
Kebun kecil kami mungkin tak sebesar ladang-ladang yang sedang digusur. Tapi ia adalah ingatan akan kemungkinan lain. Ingatan bahwa kehidupan bisa ditumbuhkan dari bawah. Dari kerja-kerja perawatan yang pelan tapi penuh cinta.
Dalam dunia yang sedang dilanda krisis iklim, pembakaran hutan, pencemaran tanah, dan banjir akibat alih fungsi lahan kita tidak bisa terus berlari dalam logika lama. Kita butuh pendekatan baru yang tidak menjadikan tanah sebagai obyek produksi tapi sebagai subjek perawatan. Kita perlu mengubah arah: dari dominasi menjadi kedekatan. Dari eksploitasi menjadi perawatan.
Dan jalan itu seperti yang telah ditunjukkan oleh perempuan-perempuan Iwul dan Rojava, bukan dimulai dari kebijakan negara atau proyek besar. Ia dimulai dari ladang kecil, dari sekop yang menyentuh tanah, dari benih yang disemai dengan harapan, dari tubuh-tubuh yang berkeringat merawat kehidupan. Jalan itu dimulai dari kebun-kebun seperti Narada—kecil, pelan, tapi terus tumbuh.
Tanah adalah ibu. Perawatan adalah kerja-kerja kehidupan. Dan perempuan, dalam tubuh dan pikirannya adalah lambang dari keberlanjutan itu sendiri. Maka dalam dunia yang sedang menuju kehancuran, perawatan adalah bentuk keberanian. Dan menanam adalah bentuk doa yang paling radikal.
Penulis: Tenu Permana
Editor: Zera Yudhistira