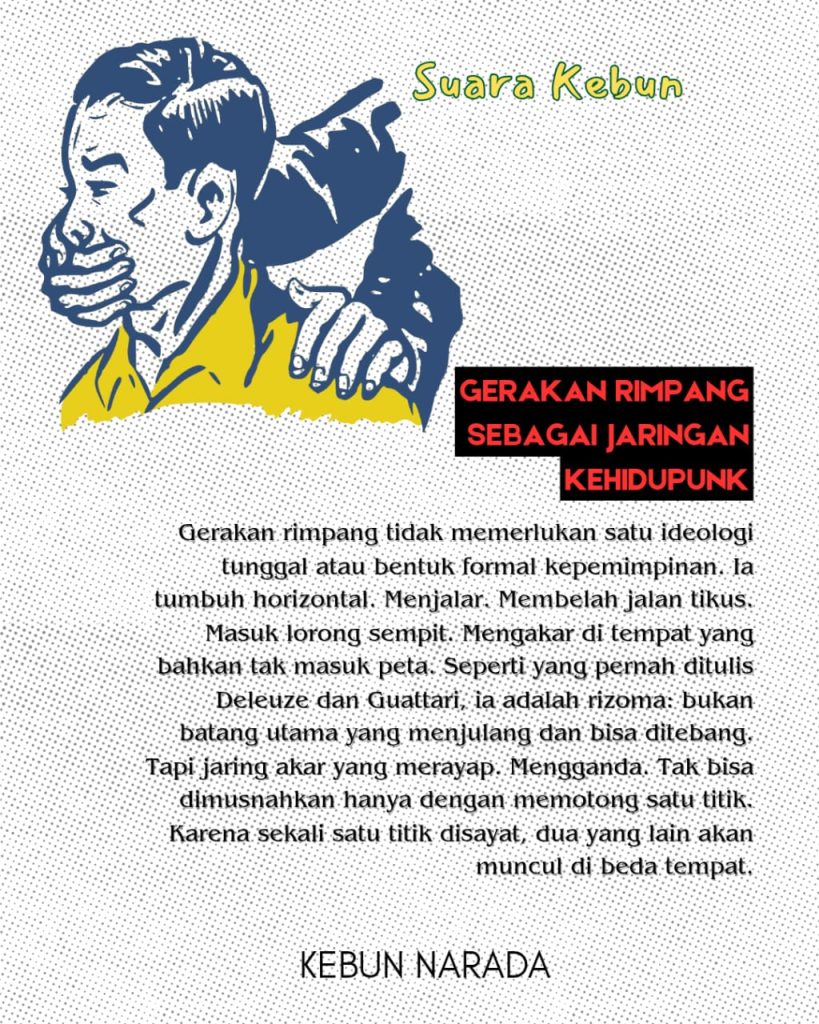GERAKAN RIMPANG SEBAGAI JARINGAN KEHIDUPUNK
Tak semua yang tumbuh membutuhkan izin. Tak semua yang bertahan harus terdaftar. Di dalam ruang kota yang dikonstruksi untuk memperkuat kontrol dan distribusi kuasa, selalu ada yang menyimpang. Bukan sebagai kesalahan, melainkan sebagai strategi bertahan. Sebab dalam sistem yang dibangun untuk menertibkan segalanya—dari arah mata angin sampai arah pikiran—menyimpang bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan.
Di kota yang segalanya punya aturan, kami belajar nyimpang. Nggak butuh izin. Nggak perlu proposal. Kami nyemai benih bukan buat dipamerkan di pameran urban farming, tapi untuk makan. Untuk menyambung hidup. Untuk ngasih makan temen-temen yang baru saja didepak dari kostan karena nggak nemu-nemu kerjaan.
Segalanya bermula dari kecewa dan perut yang lapar.
Rimpang. Itu cara kami bergerak. Bukan dari teori. Tapi dari kenyataan. Dari tanah yang terlalu sering dilewati, tapi tidak pernah dipedulikan. Dari dapur yang tetap ngebul meski tanpa subsidi. Dari kehidupan yang tak diundang masuk dalam rencana pembangunan, tapi tetap hadir, keras kepala, dan enggan hilang.
Rimpang itu tumbuh tanpa kepala. Tanpa pusat. Tapi saling nyambung. Bak akar yang menyelinap di bawah pagar beton. Tidak kelihatan, tapi kuat. Tidak rapi, tapi tahan banting. Ia tidak butuh izin untuk menjalar. Ia hanya butuh celah. Dan kota ini, betapapun liciknya ia ditata, selalu menyisakan retakan. Dan dari retakan itulah kami tersemai.
Karena bagi kami, rimpang bukan strategi. Itu naluri. Naluri bertahan. Naluri berbagi. Naluri untuk tetap hidup saat sistem yang ada justru meniadakan kehidupan. Ia bergerak bukan karena perintah, tapi karena kebutuhan. Ia tidak bertanya siapa pemimpin. Ia tidak menunggu konsensus. Ia langsung bekerja. Menggali tanah Menyiram sayur. Mengolah dapur umum , Mengantar logistik. Menyambung napas yang diputus oleh harga sewa dan daftar tunggu bantuan sosial.
Gerakan rimpang tidak memerlukan satu ideologi tunggal atau bentuk formal kepemimpinan. Ia tumbuh horizontal. Menjalar. Membelah jalan tikus. Masuk lorong sempit. Mengakar di tempat yang bahkan tak masuk peta. Seperti yang pernah ditulis Deleuze dan Guattari, ia adalah rizoma: bukan batang utama yang menjulang dan bisa ditebang. Tapi jaring akar yang merayap. Mengganda. Tak bisa dimusnahkan hanya dengan memotong satu titik. Karena sekali satu titik disayat, dua yang lain akan muncul di beda tempat.
Dan seperti itulah kami. Dipindahkan dari satu tempat, kami muncul di tempat lain. Ditekan di satu sisi, kami tumbuh di sisi yang tak diawasi. Karena kota yang mereka desain terlalu percaya pada garis lurus dan zonasi. Padahal hidup selalu berbelok. Dan kami justru tumbuh dari belokan-belokan itu.
Sebab kota yang mereka bangun bukanlah ruang untuk tumbuh bersama, tapi alat ukur keteraturan dan nilai jual. Ia adalah manifestasi paling konkret dari modernitas kapitalistik, telah menjelma jadi infrastruktur akumulasi nilai lebih. Ruang tidak lagi dimaknai sebagai tempat tinggal bersama, tapi sebagai komoditas. Ruang bukan lagi habitat, tapi investasi. Diperjualbelikan dalam meter persegi. Ditaksir bukan berdasarkan kebutuhan hidup, tapi berdasarkan potensi keuntungan. Maka, hak atas kota tidak sekadar soal akses, tetapi soal kuasa. Siapa yang berhak menentukan kota ini untuk siapa, dan siapa yang harus disingkirkan darinya.
Dalam konteks ini, gerakan rimpang tidak lahir dari proyek kebijakan. Ia tidak disponsori. Ia tidak diturunkan dari hasil rapat kementerian. Ia muncul sebagai bentuk perlawanan dari mereka yang tahu bahwa kalau menunggu negara, yang datang bukan bantuan, tapi penggusuran.
Lumbung pangan kolektif, kebun kota informal, dapur umum swadaya, koperasi liar, dan jaringan distribusi sayur berbasis solidaritas bukanlah hasil dari intervensi pembangunan. Mereka lahir dari kekosongan. Dari lubang yang ditinggalkan oleh sistem yang gagal menjalankan fungsi reproduktif sosial. Dari situasi di mana hidup tidak bisa lagi ditopang oleh upah kerja, tapi justru ditopang oleh saling jaga. Saling beri. Saling percaya.
Ruang-ruang yang kami isi adalah ruang yang disebut “tidak produktif” oleh negara dan pasar. Tapi justru di sanalah kami menanam. Di tanah yang tidak dianggap strategis. Di lorong-lorong yang tak masuk masterplan. Di sisa lahan di antara beton dan seng. Di tempat yang mereka anggap lahan tidur, kami bangunkan kehidupan. Bukan dengan kontrak, tapi dengan kompos. Bukan dengan perintah, tapi dengan kerja kolektif. Dan di situlah kota yang kami alternatifkan berkembang. Kota yang tidak berdasarkan transaksi, tapi pada reproduksi. Kota yang tidak diorganisir lewat regulasi, tapi lewat solidaritas yang membumi. Kota yang tidak menjual ruang hidup, tapi menyulam hidup agar tak tercerabut.
Namun pada akhirnya, barangkali yang kami kejar bukan sekadar keberlanjutan, bukan pula kemenangan.
Tapi kemungkinan, bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang lain. Bahwa kota tak harus dibangun di atas kompetisi, penggusuran dan ketimpangan yang diwariskan. Bahwa dari ruang yang ditinggalkan, dari tanah yang dianggap tak bernilai, dari dapur-dapur sempit yang saling menyambung, bisa tumbuh cara hidup yang tidak bergantung pada belas kasihan sistem yang kian tak peduli.
Kami tidak sedang memimpikan utopia. Kami hanya sedang menolak untuk tunduk pada distopia yang setiap hari disajikan dengan senyum birokrasi dan tarif listrik yang terus mencekik. Kami tahu dunia ini tak mudah diubah, tapi setidaknya kami bisa merawat serpih-serpih kecil dari dunia yang kami percaya. Dunia yang tumbuh dalam diam. Dalam kerja kolektif yang tak didokumentasikan. Dalam sapaan pelan dari tangan-tangan yang saling menyuapi sebelum tergantikan.
Dan barangkali inilah makna terdalam dari gerak rimpang. Ia tidak hadir untuk merebut panggung, melainkan untuk menjaga keberlanjutan hidup di balik bayang-bayang panggung. Ia tidak butuh pengakuan karena yang diperjuangkan bukanlah status, melainkan keberlangsungan. Ia tahu bahwa kekuatan tidak selalu tampak dalam gemuruh, tapi juga dalam kesetiaan menyiram tanah yang retak setiap detak.
Sebab yang kami jaga bukanlah arah. Bukakah peta. Melainkan hubungan. Kesinambungan. Maka kami tidak menunggu kompas baru. Kami berjalan tanpa peta. Tidak menuju pusat. Tidak menuju menara-menara tinggi. Tapi menuju satu sama lain. Membangun koneksi bukan untuk jaringan kekuasaan, tapi untuk jaringan kehidupan yang lebih cair. Lebih lentur. Lebih lembut. Lebih tahan terhadap guncangan kekuasaan.
Karena kami tahun, kota yang mereka bangun bukan untuk dihuni, tapi untuk dihitung. Maka kami membayangkan kota yang lain. Kota yang mengenal cukup. Kota yang tahu bagaimana rasanya berbagi meski sedang kekurangan. Kota yang tidak dibagi menurut nilai jual lahan, tapi menurut kebutuhan yang paling manusiawi. Pada rasa aman. Pada rasa tenang. Pada rasa merasakan.
Dan dari sanalah rimpang terus tumbuh. Meski pelan. Meski sunyi-sepi. Karena kami percaya, dari dalam retakan sistem yang mulai lelah menopang dirinya sendiri, akan lahir bentuk kehidupan yang lain. Bukan sekadar hidup yang berhasil bertahan, tapi hidup yang layak dirayakan. Dan itu sudah mulai terjadi.